PEMBAHASAN
1. Sejarah Singkat Keraton Mataram Islam dan Masuknya VOC di Lingkungan Keraton
Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati Ing Alogo (1584-1601) dengan pusat kerajaannya adalah Kota Gede Yogyakarta. Pada masa Senopati ini telah dimulai penaklukan kerajaan-kerajaan yang lain seperti Pajang dan Demak. Pengganti Penambahan Senopati adalah Panembahan Seda ing Krapyak (1601-1613). Panembahan Krapyak meneruskan usaha penaklukan wilayah sampai ke Jawa Timur. Namun usaha ini belum berhasil, sampai beliau meninggal dunia yang digantikan oleh putranya Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyakrokusumo (1613-1646). Sultan Agung merupakan raja terbesar dalam sejarah Mataram Islam. Sultan Agung meneruskan penaklukan daerah sekitarnya yakni Madura (1624) dan Surabaya (1625). Sultan Agung juga berusaha untuk merebut Batavia dari tangan VOC yakni pada tahun 1628 dan 1629, namun semuanya berakhir dengan kegagalan (Ricklefs, 2005: 99-107).
Sepeninggal Sultan Agung pada tahun 1646, Keraton Mataram Islam dipimpin oleh Amangkurat I. Amangkurat I (1646-1677) memindahkan istana barunya di Plered, tepat di sebelah timur laut ibukota sebelumunya. Raja ini oleh para ahli sejarah dianggap sebagai raja yang buruk perangai. Semua kelompok yang tidak mendukungnya akan dibunuhnya. Tidak ada prestasi yang dapat diukir dalam regim pemerintahan Amangkurat I ini, yang menyebabkan kewibawaan Kerajaan Mataram Islam mulai merosot. Konpirasi untuk menggulingkan raja diprakarsai oleh putra mahkota sendiri yakni Amangkurat II yang memerintahkan Trunojoyo untuk memberontak. Pada akhirnya Amangkurat I kalah dan meninggal dunia di Tegal. Sejak itu, Amangkurat II (1677-1703) menjadi Raja Mataram. Atas bantuan VOC, pada akhirnya Amangkurat II berhasil mengalahkan Trunojoyo.
Pada September 1680, Amangkurat II memindah ibu kota negara di sekitar daerah Pajang yang diberi nama Kartasura (Ricklefs, 2005:179). Pada tahun 1703, Amangkurat II mangkat dan digantikan oleh putranya Amangkurat III (1703-1708, w 1734). Namun tidak semua kerabat istana menyetujui pengangkatan Amangkurat III, salah satunya adalah pamannya sendiri Pangeran Puger. Konflik antara putra mahkota dengan pamannya sendiri ini memang sudah berlangsung lama sebelum Amangkurat II meninggal dunia. Ketika itu melicinkan jalan menjadi raja, Amangkurat II berkerjasana dengan Untung Surapati yang ketika itu menjadi musuh besar VOC. Maka, setelah Amangkurat III naik tahta, Pangeran Puger menghubungi VOC di Semarang dan menceritakan konspirasi Amangkurat III dengan Surapati. Diplomasi Pangeran Puger berhasi meyakinkan VOC dan pada Juni 1704, VOC mengakuinya Pangeran Puger sebagai Raja Mataram yang baru yang bergelar Susuhunan Pakubuwono I (1704-1719). Akhirnya pada bulan September 1705, Susuhunan Pakubuwono I berhasil mengalahkan Amangkurat III yang lari bersama dengan Surapati ke Jawa Timur (Ricklefs, 2005: 179). Pakubuwonao I mangkat digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat IV (1719-1726). Pada masa ini muncul pemberontakan dari kalangan pangeran. Lagi-lagi VOC berhasil membantu dan mempertahankan raja. Pada bulan Maret 1726, Amangkurat IV jatuh sakit dan mangkat yang kemudian digantikan putranya yang bergelar Pakubuwono II (1726-1749). Pada masa Pakubuwono II terjadi kerusuhan besar yang dikenal sabagai ”Geger Pecinan” yang menjadi penyebab utama kepindahan Keraton Kartosura ke Keraton Surakarta.
2. Kerusuhan di Keraton Kartosura
Geger Pecinan di Kartosura tidak dapat dilepaskan oleh peristiwa pembantaian orang-orang Tionghoa oleh VOC di Batavia (Jakarta). Pembantaian itu disebabkan oleh akumulasi konflik antara orang-orang Eropa terhadap komunitas Tionghoa di Batavia. Konflik antara orang-orang Eropa dan orang-orang Tionghoa di Batavia adalah konflik khas perkotaan dimana para etnis yang hidup berdampingan saling bersaing dalam mencari penghidupan. Kehadiran sejumlah besar orang-orang Tionghoa dari China Daratan menyebabkan suasana Batavia menjadi semakin panas. Pada tahun 1740, jumlah Tionghoa diperkirakan telah mencapai sekitar 15.000 jiwa atau sekitar 17% total penduduk di Batavia. Kebanyakan Tionghoa pendatang itu tidak dapat memperoleh pekerjaan dan sebagian dari mereka menjadi sumber kerentanan sosial dengan semakin meningkatnya aksi-aksi kejahatan di sekitar Batavia (Ricklefs, 2005: 208). Untuk membatasi semakin meningkatnya komunitas Tionghoa, VOC membuat larangan untuk mencegah banyaknya orang-orang Tionghoa datang ke Batavia. Sementara, bagi yang telah tinggal di Batavia dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, VOC menangkap mereka dan membuangnya ke Ceylon (Srilangka) atau Kaap de Goede Hoop (Afrika). Yang dibiarkan tinggal di Batavia adalah orang-orang Tionghoa yang telah mempunyai izin tinggal. Untuk mendapatkan izin tinggal, orang-orang Tionghoa harus membayar kepada VOC. Bahkan ada beberapa pembesar VOC memeras orang-orang Tionghoa dengan meminta bayaran yang sangat mahal. Ini tentu saja meresahkan komunitas Tionghoa di Batavia. Apalagi ketika beredar isu bahwa orang-orang Tionghoa yang ditangkap dan dibawa ke Srilangka dan Afrika itu, sebenarnya di tengah jalan, mereka di lemparkan ke laut, menyebabkan keresahan semakin menjadi-jadi. Situasi ini mendorong orang-orang Tionghoa bersiap melakukan melakukan penentangan kepada VOC (Liem, 2004: 35).
Pada 7 Oktober 1740, gerombolan-gerombolan orang Tionghoa yang berada di luar kota melakukan penyerangan dan pembunuhan beberapa orang Eropa. Agar orang-orang Tionghoa di dalam kota tidak bergabung dalam kerusuhan itu, VOC melakukan jam malam dan penggeledahan kepemilikan senjata di rumah-rumah orang Tionghoa. Ternyata penggeledahan atas rumah-rumah Tionghoa tidak terkendali lagi, tembakan membabi buta dilakukan oleh VOC. Pada 9 Oktober 1740 dimulailah pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia. Diperkirakan orang-orang Tionghoa yang terbunuh sebanyak 10.000 orang. Perkampungan Tionghoa dirampok dan dibakar delapan (8) hari hari. Perampokan baru berhenti setelah VOC memberi premi kepada tentaranya untuk menghentikan penjarahan dan kembali kepada tugas rutinnya. Sementara, orang-orang Tionghoa yang berhasil lolos dari pembantaian di Batavia melarikan diri ke timur, menyusuri sepanjang daerah pesisir bergabung dengan komunitasnya di Jawa Tengah untuk melakukan perlawanan terhadap VOC lebih lanjut (Ricklefs, 2005: 208).
Pembantaian komunitas Tionghoa di Batavia berdampak sangat besar bagi perkembangan politik, ekonomi dan sosial di Jawa. Pembantaian ini memunculkan solidaritas yang luar biasa untuk melawan VOC baik kalangan etnis Tionghoa maupun etnis Jawa seperti nanti diwakili oleh Pakubuwono II. Beberapa komunitas Tionghoa di pesisir juga langsung melakukan perlawanan kepada VOC. Pada Mei 1841, komunitas Tionghoa melakukan penyerangan pos VOC di Juwana. Markas besar VOC di Semarang dan beberapa pos lain di pesisir dikepung. Pada Mei 1741, VOC terpaksa meninggalkan posnya di Demak. Sementara pada Juni 1741, pos VOC di Rembang hendak dikosongkan, tetapi usaha itu gagal, pada bulan Juli personel VOC di sana di bantai (Ricklefs, 2005: 210).
Sementara itu respons terhadap pembantaian orang-orang Tionghoa juga ditunjukkan oleh Pakubuwono II. Banyak yang menganggap bahwa Keraton Mataram ini memanfaatkan konflik VOC dengan Tionghoa, namun jelas bahwa dalam konteks keberanian melawan penjajah respons Pakubuwono II ini merupakan langkah positif. Dan ini mungkin juga salah satu bentuk solidaritas Raja Mataram terhadap kelompok Tionghoa. Sebenarnya di kalangan istana sendiri telah berkembangan dua pendapat yang bersifat pro dan kontra terhadap rencana Pakubuwono II menyerang VOC bergabung dengan komunitas Tionghoa. Pandangan pertama seperti diutarakan kelompok Patih Natakusuma memilih melawan VOC sebagai sebuah langkah strategis dengan jalan bergabung dengan komunitas Tionghoa. Kelompok lain dipimpin oleh penguasa daerah pesisir yang berpendapat bahwa dalam peperangan VOC dan Tionghoa, pada akhirnya akan dimenangkan oleh VOC. Maka mereka menganjurkan tidak perlu tergesa-gesa, sebaiknya menunggu sampai VOC terdesak dan meminta bantuan Mataram.
Dua pertimbangan ini menyebabkan Pakubuwono II sempat ragu-ragu, namun pada akhir Raja Mataram ini lebih memilih pandangan yang pertama yakni segera melakukan penyerangan kepada VOC. Pada November 1741, Pakubuwono II mengirim pasukan dan artileri ke Semarang sebanyak 20.000 orang dan 30 pucuk meriam yang bergabung 3.500 orang Tionghoa mengepung Markas Besar VOC di Semarang. Selain itu, Pakubuwono II juga menyerang pos VOC di Kartasura yang berhasil membunuh Kapten Johansen van Nelsen dan menghancurkan markas itu (Ricklefs, 2005: 211). Dalam posisi sulit itu, akhirnya VOC mendatangkan bala tentaranya dari Batavia dan meminta bantuan Cakraningrat IV dari Madura. Mereka berhasil memukul mundur kepungan Tionghoa yang dibantu Mataram di Markas VOC Semarang. Bahkan Cakraningrat IV berhasil mengalahkan para pejuang Tionghoa di wilayah timur. Setelah kekalahannya itu, Pakubuwono II baru menyadari bahwa pilihannya untuk mendukung komunitas Tionghoa melawan VOC adalah sebuah tindakan yang keliru. Untuk itu Pakubuwono segera memohon ampun kepada VOC. VOC mengabulkan dan mengirim utusan yang dipimpin Kapten Van Hohendorff ke Kartasura untuk melakukan perundingan. Sementara, Pakubuwono II mengirim juru runding yang dipimpin oleh Patih Natakusuma ke VOC Semarang, namun VOC menangkap Patih itu dan membuang ke luar negeri. Penangkapan dan pembuangan Patih Natakusuma atas seizin Pakubuwono II (Ricklefs, 2005: 212).
Perubahan sikap Pakubuwono II menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai kalangan. Para pejuang anti VOC baik dari kalangan Jawa maupun Tionghoa merasa telah dikhianati oleh Raja. Situasi ini memunculkan perlawanan pejuang yang lebih hebat baik kepada VOC maupun Pakubuwono II. Bahkan beberapa pangeran istana yang tidak puas dengan Pakubuwono II pun bergabung dalam makar ini diantaranya Pangeran Mangkubuni (kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono I) dan Raden Mas Said (kelak menjadi Pangeran Adipadi Mangkunegara). Isu perlawanannya pun berubah dari anti VOC menjadi anti Pakubuwono, maka sasaran penyerangannya adalah Keraton Pakubuwono II di Kartasura. Pada tahun awal 1742, para pemberontak itu mengangkat salah seorang pangeran cucu laki-laki dari Amangkurat III yang baru berusia 12 tahun yang bernama Mas Gerendi yang bergelar Amangkurat V atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kuning. Sunan Kuning adalah sebutan sunan yang diangkat oleh komunitas Tionghoa. Pemberontakan ini berhasil merebut Keraton Kartasura pada bulan Juli 1742, dan Pakubuwono II lari ke Panaraga. Kenaikan Mas Garendi sebagai Raja Pemberontak yang diangkat oleh Komunitas Tionghoa dan berhasil merebut Keraton Kartosuro telah mengguncangkan sendi-sendi kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Tidak saja dari sudut politik, tetapi juga dapat dipandang dari sudut budaya. Bahkan kenaikan Mas Garendi itu dihubungkan dengan keyakinan orang Jawa terhadap Ramalan Jayabaya.
Ramalan Jayabaya pernah meramalkan bahwa nanti “orang asing” akan memimpin Jawa “seumur Jagung”. Bahkan seorang intelektual Indonesia yang cukup rasional pun seperti Tan Malaka percaya dengan itu (2000: 16): “... Jawa sesungguhnya dikungkung oleh ramalan Empu Sedah: orang asing akan memimpin.....semua perang saudara ini, besar atau kecil, untuk kepentingan bangsa asing, dalam waktu singkat berakhir dengan kemenangan Tionghoa-Jawa bernama Mas Garendi.” Secara kebudayaan kemenangan politik Tionghoa di Kartosuro itu semakin menorehkan luka bagi orang Jawa. Raja dan Kerajaan merupakan simbol penting masyarakat Jawa pada masa itu yang berhasil dikalahkan oleh orang Tionghoa. Kemenangan Mas Garendi merupakan pengulangan sejarah di mana muncul Raja yang didukung oleh orang-orang Tionghoa. Sebelumnya pernah ada Raja dari keturunan Tionghoa-Jawa yang bernama Raden Patah yang berhasil mendirikanKerajaan Demak dan mengalahkan Kerajaan Majapahit.
Dalam pelariannya, Pakubuwono II meminta bantuan kepada VOC dengan memberikan konsesi, jika bisa kembali menjadi Raja, maka akan memberikan wilayah pesisir Pulau Jawa kepada VOC. VOC menyetujui dan meminta bantuan kepada Cakraningrat IV untuk melawan para pemberontak. Bersama dengan lasykar Madura, Cakraningrat IV berhasil mengalahkan pemberontak. Dan atas permintaan VOC, Cakraningrat IV menyerahkan Keraton Kartosura kepada Pakubuwono II. Setelah Pakubuwono II kembali berkuasa segera merealisasi konsesi-konsesi kepada VOC diantaranya adalah(1) kedaulatan penuh atas Madura Barat, Surabaya, Rembang, Jepara; (2) Raja menyerahkan 5000 koyan (sekitar 8.600 metrik ton) beras setiap tahun untuk selama-lamanya; (3) Patih hanya dapat dipilih dengan persetujuan VOC; (4) ada sebuah garnisun VOC di istana; (5) orang Jawa tidak boleh berlayar ke mana pun di luar Jawa, Madura dan Bali (Ricklefs, 2005: 214). Ketika kembali ke Kartasura, pada 21 Desember 1742 Pakubuwono II, mendapati istana dalam keadaan rusak parah. Yasadipura –Pujangga Istana- dalam Babad Giyanti menceritakan suasana memilukan ketika Raja kembali ke istananya yang telah rusak “ Raja tampak kelihatan seperti biasanya ketika istana masih kaya raya dan jaya. Tetapi dalam hati sangat bersedih memikirkan keadaan istana beserta segala isinya porak poranda, laksana hilang dibakar oleh musuh yaitu Cina...” Maka, Raja meminta kepada Patih Pringgalaya dan Sindureja serta Van Hohendorf (VOC) segera mencari tempat untuk membangun keraton baru.
3. Membangun Keraton Surakarta
Keinginan untuk membangun keraton baru, setelah Karaton Kartosuro rusak parah, bagi Pakubuwono II bukan perkara mudah. Terutama sejak beliau sempat tersingkir dari Keraton Kartosura dan atas bantuan VOC bertahta kembali di Keraton Katosura. Yang jelas mulai saat itu setiap tindakan dan langkah Raja harus mendapatkan izin dari VOC. Beberapa alternatif tempat yang baru telah disampaikan Raja kepada VOC salah satunya adalah kawasan Tingkir Salatiga. Van Hohendorff melaporkan kepada Kantor Pusat VOC di Batavia tentang keinginan Raja untuk memindahkan Ibu Kotanya pada tahun 1742. Setahun kemudian ada surat dari Gubernur Jenderal Johanes Thedens yang isinya: “Raja berkehendak memindahkan istana: wilayah Tingkir di daerah Salatiga yang direncakanan Raja, sepertinya sangat sesuai dengan yang diharapkan”.
Namun wacana untuk pindah ke wilayah Utara Kartosura tidak terwujud, kendati pun mungkin di daerah itu juga terdapat sungai besar yang mengalir dari selatan ke utara yakni Sungai Tuntang yang mengalir dari Salatiga ke Demak. Namun rupanya Pakubuwono II masih ragu-ragu dengan alternatif tempat di kawasan Tingkir Salatiga itu. Justru beliau pada akhirnya meminta Patih Pringgalaya dan Sindureja serta Van Hohendorf mencari tempat ke daerah selatan. Akhirnya Ketiga orang itu mencoba mencari alternatif daerah ke wilayah Selatan. Ada tiga tempat yang menjadi alternatif keraton yang baru yakni Desa Kadipolo, Sonosewu dan Sala. Menurut Tumenggung Honggowongsi jika karaton dibangun di Desa Kadipolo dikemudian hari akan makmur, namun karaton akan cepat rusak dan banyak perang saudara. Bahkan Tumenggung Honggowongso meramalkan, jika karaton berdiri di Kadipolo hanya akan berusia maksimal 100 tahun. Sebaliknya jika karaton didirikan di Desa Sonosewu yang berada di sebelah timur Bengawan Sala, menurut Honggowongso tempat ini kurang cocok dan diramalkan hanya akan berusia 120 tahun, banyak perang dan akan kembali ke Agama Hindu Budha.
Sementara, kalau keraton didirikan di Desa Sala, menurut Honggowongso akan menjadi keraton besar dan dapat berumur lebih dari 200 tahun. Namun di luar aspek-aspek spiritual itu, pemilihan Desa Sala juga mengandung aspek strategis geografis. Tampaknya dari pihak VOC mempunyai visi yang cukup jelas tentang sebuah ibu kota negara yang baru yakni harus dekat dengan sungai besar sebagai sarana transportasi. Seperti telah disebutkan di atas, usulan pertama untuk ibu kota baru adalah daerah Tingkir (Salatiga) yang dekat dengan Sungai Tuntang yang mengalir dari Salatiga ke Demak. Pilihan kedua adalah Bengawan Sala yang berhulu di Pegunungan Seribu (Wonogiri) mengalir dari selatan ke utara sampai ke Bojonegoro dan Surabaya. Maka, dibandingkan Sunga Tuntang, Bengawan Sala lebih menjangkau wilayah yang lebih luar ke arah timur. Apalagi Bengawan Sala ketika itu, sudah merupakan bandar yang relatif cukup besar yang telah menjadi persinggahan pedagang dari Gresik dan Surabaya sejak zaman Pajang. Selain itu, di sekitar Bengawan Sala sudah terdapat permukiman multi etnis seperti Arab, Tionghoa, Madura dan juga kantor-kantor perdagangan VOC. Pembangunan Keraton Surakarta memakan waktu sekitar 3 tahun yang selesai pada akhir tahun 1745. Penanggungjawab utama pembangunanan adalah Van Hohondorff yang tentu saja menggunakan tenaga-tenaga arsitek dari Belanda. Sementara para pekerja terdiri atas Wadana, Kaliwon, Panewu, Mantri, Lurah, Bekel dan Jajar. Perpindahan resmi Raja dari Kartosura ke Surakarta terjadi pada 17 Pebruari 1746 yang merupakan dianggap berdirinya Kota Surakarta Hadiningrat.
4. Perpecahan Keraton Kerajaan Mataram
Perpindahan Keraton dari Kartosura ke Surakarta ternyata tidak menyurutkan konflik politik di Kerajaan Mataram Islam itu. Beberapa pemberontak yang melawan Pakubuwono II masih berjalan seperti antara lain Raden Mas Said yang bermarkas di Sokawati (Sragen). Untuk meredam pemberontakan itu, Raja mengumumkan bahwa siapa pun yang dapat mengusir mereka dari Sokawati akan diberi hadiah bertupa tanah sejumlah 3.000 cacah. Pangeran Mangkubumi bersemangat menerima tawaran itu. Pada tahun 1746 dia berhasil mengusir Raden Mas Said dari Sukawati dan menuntut hadiah yang ditawarkan oleh Raja. Akan tetapi, musuh lamanya di istana, Patih Pringgalaya (1742-55) membujuk Raja untuk menahan hadiah itu. Di tengah situasi yang genting itu, datanglah Gubernur Jenderal VOC dari Batavia Van Imhoff yang semakin memperkeruh suasana (Moedjanto, 1994:12). Kedatangan Van Imhoff sebenarnya adalah mengurus kepentingan VOC tentang hak atas pesisir Pulau Jawa sebagai bagian dari perjanjian dengan Pakubuwono II pada tahun 1743. VOC mempunyai hak atas daerah yang sempit di sepanjang wilayah pesisir dan semua sungai yang mengalir ke laut.
Namun yang didinginkan oleh VOC lebih dari itu. VOC berkeinginan menguasai seluruh pelabuhan di wilaya pesisir. Akhirnya Pakubuwono II terpaksa mengabulkan keinginan VOC dengan uang sewa sebesar 20.000 real per tahun. Padahal biasanya para pejabat sjahbandar akan setor ke Karajaan sebesar 94.176 real pertahun. Jadi jumlah yang disepakatai oleh VOC itu sangat sedikit dan merugikan Kerajaan. Ketika Pakubuwono II memberitahukan hal ini kepada para penasehat dan pangeran, sebagian besar dari mereka tidak setuju termasuk Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi beranggapan bahwa Raja terlalu lemah di bawah tekanan VOC.
Ketidaksetujuan Mangkubumi itu menyebabkan ketidaksukaan Van Imhoff kepadanya. Maka, dalam kasus pemberian wilayah Sukowati kepada Mangkubumi, Van Imhoff sependapat dengan Patih Pringgalaya mendesak hal itu jangan diserahkan. Dalam suatu paseban di istana, Van Imhoff mengkritik secara langsung Mangkubumi yang menganggapnya terlalu ambisius dan tidak tahu berterima kasih kepada Raja Kecaman Van Imhoff di muka umum itu sangat menyinggung Pangeran Mangkubumi yang memicu lahirnya pemberontakan besar di Keraton Surakarta pada Mei 1746 (Ricklefs, 2005: 218-219). Setelah peristiwa paseban itu, pada malam harinya Pangeran Mangkubumi beserta pengikutnya meninggalkan Surakarta menuju Sukawati bergabung dengan pasukan Raden Mas Said melancarkan pemberontakan. Alasannya karena Raja ingkar janji dan Belanda yang dianggap murang tata atau kurang ajar. Kolaborasi Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said dalam waktu yang singkat mendapatkan pengikut yang banyak. Pada tahun 1747, Mangkubumi memimpin pasukan yang diperkirakan 13.000 prajurit, termasuk diantaranya 2.500 prajurit kavaleri.
Pada tahun 1748, Mangkubumi dan Raden Mas Said menyerang Surakarta, kendati pun tidak berhasil merebut kota itu. Pada saat ini pasukan VOC dan Kerajaan dalam keadaan lemah, sehingga tidak dapat mengalahkan pemberontak dan hanya dapat bertahan di Ibu Kota Negara (Ricklefs, 2005: 219). Di tengah pemberontakan itu, pada penghujung 1749, Pakubuwono II jatuh sakit. Gubernur Jenderal VOC yang baru yakni Von Hohendorff (1748-54), utusan VOC yang membantu Pakubuwono II merebut kekuasaannya kembali di Kartsura, berangkat ke Surakarta untuk mengawasi berlangsungnya pergantian kekuasaan. Bertemu dengan kawan lama, Pakubuwono II mengusulkan agar Von Hohendorff sendirilah yang mengambil alih kepemimpinan atas negara. Maka, dibuatlah perjanjian dengan VOC yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1749 yang menyerahkan kedaulatan atas seluruh kerajaan kepada VOC. Raja wafat sembilan hari kemudian. Pada 15 Desember 1749, Van Hohendorff mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai Susuhunan Pakubuwono III (1749-88).
Pada waktu bersamaan, Pangeran Mangkubumi di markasnya Yogyakarta juga dinobatkan oleh pengikutnya sebagai Susuhunan Pakubuwono tandingan. Sementara, Raden Mas Said sebagai menjabat sebagai Patih Mangkubuminya. Dengan demikian sejak akhir 1949 itu, Jawa terbagi menjadi dua, antara seorang raja pemberontak dan seorang raja yang didukung oleh VOC. Perbedaannya sekarang ialah pemberontak sangat kuat, sedangkan raja dukungan VOC jauh lebih lemah, sehingga pemberontakan sulit dihancurkan (Ricklefs, 2005: 220). Pada tahun 1752, terjadi perpecahan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Konflik dua pangeran pemberontak itu di satu sisi memperberat VOC namun di sisi lain merupakan peluang VOC untuk menyelesaikan perang berkepanjangan itu. Pada tahun 1754, Gubernur Jenderal Nicolaas Hartingh (1754- 61) menawarkan perundingan kepada Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi dijanjikan akan mendapat separoh dari Kerajaan Mataram; mendapatkan separoh dari pembayaran uang sewa 20.000 real tiap tahun; dan VOC bersedia membantu melawan Raden Mas Said. Pakubuwono III tidak dimintai pendapat tentang pembagian kerajaan ini, tetapi dia juga tidak punya pilihan lain kecuali menyetujuinya. Pada tanggal 13 Februari 1755, Perjanjian Gianti ditandatangani dan VOC mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Peristiwa ini disebut sebagai Palihan Nagari. (Ricklefs, 2005: 221).
5. Perjanjian Giyanti
Pada tanggal 13 Februari 1755, perjanjian Giyanti ditandatangani, dan VOC mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I, penguasa separuh wilayah Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC yang diwakili oleh W. van Ossenberch, J.J. Steenmulder, C. Donkel, dan W. Fockens, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III, dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu kelompok Pangeran Sambernyawa tidak ikut sehingga Pangeran Mangkubumi memutar haluan dengan menyeberang dari kelompok pemberontak ke kelompok pemegang legitimasi kekuasaan untuk memerangi pemberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 tersebut secara de facto dan de jure menandai berakhirnya Kesultanan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Giyanti (ejaan Belanda) yang sekarang terletak di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, sebelah tenggara Karanganyar, Jawa Tengah. Poin-poin dari perjanjian Giyanti sebagai berikut :
Pasal 1
Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwana Senapati ing Alaga 'Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah di atas separo dari Kesultanan Mataram yang diberikan kepada beliau dengan hak turun-temurun pada pewarisnya, dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundoro.
Pasal 2
Akan senantiasa diusahakan adanya kerja sama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan.
Pasal 3
Sebelum pepatih dalem (rijks-bestuurder) dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada VOC di tangan gubernur. Pepatih dalem adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dengan persetujuan dari residen atau gubernur.
Pasal 4
Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan pepatih dalem dan bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC.
Pasal 5
Sri Sultan akan mengampuni bupati yang memihak VOC dalam peperangan.
Pasal 6
Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwana II kepada VOC dalam kontraknya tertanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, VOC akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 real tiap tahunnya.
Pasal 7
Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwana III sewaktu-waktu diperlukan.
Pasal 8
Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada VOC.
Pasal 9
Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749.
Penutup
Perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh N. Hartingh, W. van Ossenberch, J.J. Steenmulder, C. Donkel, dan W. Fockens dari pihak VOC.
Pada perjanjian Gianti itu ditetapkan bahwa baik Sunan Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I mendapatkan wilayah negara agung di sekitar wilayah keraton masing-masing sebesar 53.100 karya (bahu atau cacah). Namun untuk daerah-daerah mancanegara atau daerah kekuasaan di luar negara agung, Sultan Hamengkubuwono I mendapatkan daerah sedikit lebih luas dari pada yang diterima Sunan Pakubuwono III. Kemungkinan karena daerah yang diterima Sultan kurang subur dibandingkan yang diterima Kasunanan. Daerah-daerah mancanegara yang masuk Kasunanan Surakarta adalah Jagaraga, Panagara, separoh Pacitan, Kediri, Blitar, Ladaya, Srengat, Pace (Nganjuk-Berbek), Wirasaba (Mojoagung) Blora, Banyumas dan Kaduwang. Sementara daerah mancanegara yang masuk Kasultanan Yogyakarta adalah Madiun, Magetan, Caruban, separoh Pacitan, Kertasana, Kalangbret, Ngrawa (Tulungagung), Japan (Mojokerto), Jipang (Bojonegoro), Teras Karas (Ngawen), Kedu, Sela Warung (Kuwu Wirasari) dan Grobogan. Secara lebih jelas lihat peta di bawah ini :
Gambar I : Pembagian Mataram dan Manca Nagara pada tahun 1757
Sumber : Arsip Kesultanan Ngayogyakarta.
Pembagian daerah ini disesuaikan dengan kepentingan VOC dan untuk melemahkan Kasunanan maupun Kasultanan. Dengan wilayah yang terpencar-pencar itu, kedua kerajaan itu tidak dapat mengorganisasikan kekuasaannya secara optimal dan akan selalu terjadi konflik perbatasan di antara dua kerajaan itu. Dalam kejadian perpecahan di antara elite bangsawan Keraton Mataram dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian Giyanti diantara elitye bangsawan keraton yang bertikai, ini menggambarkan kegagalan kebijakan VOC di Jawa. Sejak campur tangan militer mereka yang pertama hampir 80 tahun lalu, VOC sebagai perpanjangan tangan pemerintahan Belanda di Eropa berusaha menciptakan stabilitas dengan cara mempertahankan seorang raja di atas tahta Mataram yang akan memerintah seluruh Jawa demi kepentingan Belanda. Mereka baru menyadari bahwa bukannya menikmati stabilitas, mereka malah terus-menerus menghadapi banyak pertempuran untuk kepentingan raja-raja yang mereka dukung, dengan biaya yang sangat memberatkan. VOC segera mengetahui bahwa pembagian kerajaan memungkinkan dijalankannya kebijakan divide et Impera, akan tetapi, pada paruh kedua abad XVIII, VOC sedang dalam keadaan tidak mampu, dilanda korupsi, dan menghadapi kesulitan keuangan sehingga peluang tersebut jarang membuahkan keberhasilan.
Sementara itu, keadaan yang dihadapi Hamengkubuwana I lebih menguntungkan dibandingkan dengan raja-raja lain selama beberapa generasi, dan diapun memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Pada tahun 1755, Hamengkubuwana I pindah ke Yogyakarta, dia membangun sebuah istana pada tahun 1756, dan memberikan kota ini dengan nama baru, yaitu Yogyakarta. Tetapi sultan baru ini menghadapi rintangan-rantangan berat. Masih ada raja lain di Surakarta, Pakubuwana III. Masalah yang timbul akibat kehadiran dua raja, karena teori legitimasi jawa didasarkan pada pemerintahan hanya seorang raja yang memiliki kekuatan supernatural, tidak dapat diselesaikan selama beberapa dekade. Agaknya Hamengkubuwana I berpikir bahwa Pakubuwana III tidak akan bertahan lama, karena pada tahun 1755 hampir tidak seorang pun pembesar di Surakarta yang mendukungnya. Akan tetapi, setelah perjanjian Giyanti banyak pembesar kerajaan, yang sebelumnya kabur dari istana kembali ke Surakarta. Untuk pertama kalinya, Pakubuwana III menjadi saingan berat dalam mencari dukungan golongan elite. Hal ini mengawali suasana permanen perpisahan kedua istana tersebut.
Seiring berlalunya waktu, generasi tua yang telah merancang pembagian kerajaan yang peramanen itu mulai ditantang oleh generasi muda yang baru muncul. Di Yigyakarta, putra mahkota memperoleh kekuasaan yang lebih besar, yang kadang-kadang menimbulkan perasaan tidak senang pada diri ayahnya. Pemerintahannya kelak sebagai sultan hamengkubuwana II hampir tidak dapat dikatakan berhasil, tetapi ketika kekuasaannya mulai bertambah besar pada tahun 1770-an dan 1780-an, penampilannya seperti orang yang mempunyai bakat yang hebat. Dia mengetahui kelemahan militer VOC. Ketika pengaruhnya di istana semakin besar dan kesultanan semakin lama semakin kuat, makmur, stabil, dan nyata dalam militer yang menonjol di Jawa Tengah, maka perhatiannya terhadap VOC semakin lama semakin berkurang. Tetapi berbeda kebijakan dengan ayahnya, yaitu Hamengkubuwana I yang tetap mempertahankan aliansinya dengan VOC.
Sementara di Surakarta, masalah-masalah intern terus berkembang, ketidakcakapan Pakubuwana III secara umum, berbagai persekongkolan istana, dan perilaku pejabat-pejabat VOC yang buruk mulai mengancam keamanan dan stabilitas Surakarta. Pihak Belanda sepenuhnya mempercayai kesetian Pakubuwana III, tetapi mulai mencemaskan kondisi kerajaannya yang nyata-nyata sangat lemah. Pakubuwana III dan para bangsawan tidak pernah mempercayai Mangkunegara I dan cenderung menyalahkannya atas timbulnya ketegangan di Surakarta. Akan tetapi, Mangkunegara I mulai menunjukkan kesetian dan kerjasamanya yang lebih besar kepada Pakubuwana III maupun VOC pada tahun 1780-an, agaknya dengan harapan agar mereka bersedia menetapkan keturunan dari Mangkunegara I sebagai pewaris kedudukkannya. Ujian besar pertama terhadap ketahanan pembagian kerajaan terjadi ketika Pakubuwana III wafat pada tahun 1788 dan kedudukannya sebagai susuhunan Surakarta digantikan oleh putranya yang berumur 19 tahun, yaitu Pakubuwana IV. Dia membawa aspirasi-aspirasi yang tidak realitas dan senantiasa tidak mampu menilai lingkungan politiknya di istana yang diliputi ketegangan dan persengkongkolan, di mana beberapa personel VOC yang paling korup dan tidak cakap menjalankan tugas mereka.
Pada awal tahun 1789, Pakubuwana IV mulai mengangkat suatu kelompok baru yang disenangi pada jabatan-jabatan yang tinggi. Orang-orang ini menganut ide-ide keagamaan yang ditentang hierarki keagamaan yang sudah mapan di Surakarta. Mereka meyakinkan Raja agar beranggapan bahwa Surakarta deapat menjadi kerajaan Jawa yang lebih senior, dan dengan demikian meniadakan asas kesataraan yang mendasari pembagian permanen antara Surakarta dan Yogyakarta. Istana Yogyakarta merasa yakin bahwa Pakubuwana IV sedang merencanakan perang untuk mempersatukan kembali kerajaan. Sesungguhnya, langkah militer tidak diambil, tetapi dengan mendesak VOC agar mengakui kedudukan utama Surakarta. Desas-desus mulai tersebar, Mangkunegara I mencemaskan masa depannya sendiri dan keturunannya. Yogyakarta merasa khawatir kan stabilitas pembagian kerajaan dan tokoh-tokoh terkemuka Surakarta yang tersisih mencemaskan nasib mereka dan nasib kerajaan. Mereka semua mulai berusaha mengajak VOC agar mau bergabung dengan mereka melawan Pakubuwana IV.
Sementara itu, istana Yogyakarta semakin menyebarkan rumor yang lebih menggemparkan VOC. Dengan cara seperti ini, istana Yogyakarta berhasil meyakinkan orang-orang Belanda bahwa diperlukan langkah-langkah militer untuk menghentikan rencana-rencana Pakubuwana IV. Baik Hamengkubuwana I maupun Mangkunegara I sama-sama percaya bahwa ancaman yang mungkin timbul dari sejumlah rencana Pakubuwana IV itu akan sedemikian dahsyat, sehingga untuk pertama kalinya dalam hampir 40 tahun, mereka bekerja sama. Kini Mangkunegara I menerima 4.000 real setiap tahun dari VOC untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan pada Pakubuwana IV dan untuk memastikan dukungannya terhadap tindakan-tindakan VOC.
Pada November 1790, musuh-musuh Pakubuwana IV mulai mengepung istana. Beberapa prajurit dari Yogyakarta dan daerah Mangkunegara I mengambil alih posisi di surakarta. VOC mengirimkan ratusan serdadu Madura, Bugis, Melayu dan Eropa ke bentengnya yang berada di dalam kota. Para pangeran dan pejabat tinggi Surakarta menambah tekanan terhadap Pakubuwana IV supaya menyingkirkan penasehat-penasehatnya dan meninggalkan rencana-rencana mereka sebelum mereka membuat kerajaan hancur. Sultan Hamengkubuwana I mulai berpikir bahwa penggabungan Surakarta sekarang sudah memungkinkan dan dia mengajukan permintaan kepada VOC agar putra mahkotannya dijadikan raja di Surakarta, bila Pakubuwana IV dimakzulkan. Tetapi VOC menolak permintaan itu karena diam-diam telah memutuskan untuk mengakui Mangkunegara I sebagai raja Surakarta seandainya Pakubuwana IV dimakzulkan. Kemudian, pada tahun 1792 VOC juga menetapkan bahwa keturunan Mangkunegara I akan mewarisi daerah kekuasaannya yang terdiri atas 4000 cacah, dengan demikian daerah kadipaten Mangkunegara menjadi suatu lembaga yang permanen.
Krisis 1790 menghasilkan kepuasan bagi VOC, karena tidak jadi mengeluarkan biaya perang dan generasi tua mempunyai pengaruh lagi di Surakarta. Pembagian yang permanen atas Jawa Tengah berhasil dipertahankan dan kepentingan-kepentingan yang menopang dan menguntungkan Belanda tetap dipertahankan, bahkan para anggota keluarga terdekat seorang raja dan para pegawai istana pun akan menentang usaha sang raja untuk merusak kepentingan Belanda di kerajaan.
Beberapa tahun setelah krsisi 1790, hubungan Belanda dengan Jawa dapat dikatakan agak stabil. Namun hubungan yang harmonis itu berubah menjadi hal yang mencemaskan, tak kala Sultan Hamengkubuwana II naik tahta menggantikan ayahnya. Pada bulan maret 1792, Hemengkubuwana I wafat pada usia 80 tahun setelah menjadikan Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan yang makmur, permanen dan kuat. Dia mewariskan suatu tradisi kejayaan yang ingin diteruskan oleh putranya yang kini bergelar Sultan hamengkubuwana II. Pemerintahan Hamengkubuwana II, yang mulai merusak mufakat golongan elite yang sangat penting artinya bagi kekuatan dan stabilitas. Sultan ini bertikai dengan saudara-saudaranya, terutama dengan pangeran Natakesuma (1764-1829) yang cerdik, cakap dan berpengaruh di istana. Sebagian besar penasihat dan pejabat Hamengkubuwana I sudah meninggal dunia atau berusia sangat lanjut, dan Hamengkubuwana II segera mengganti mereka dengan orang-orangnya sendiri yang disukainya tetapi yang kurang cakap. Patih ayahnya yang cakap, Danureja I (1755-1799), diganti oleh cucunya, Danureja II (1799-1811). Dia tidak efisien dan segera menggalang persekutuan yang erat dengan suatu klik istana yang mengelilingi putra mahkota (kelak bergelar Hamengkubuwana III).
Sistem perpajakan dan kerjapaksa yang diberlakukan Sultan dengan cepat menjadi semakin menindas. Proyek-proyek pembangunannya di istana meletakkan beban kerja yang sangat berat terhadap rakyat dari daerah-daerah luar (mancanegara). Penghinaanya terhadap kelemahan VOC segera mengakibatkan semakin memburuknya hubungan Yogyakarta dengan orang-orang Belanda yang berada di istananya. Dan ketiga orang isterinya menjadi semakin berpengaruh sebagai penengah persengkongkolan istana. Dari semua keadaan itu, perasaan tidak tentu dan tidak puas semakin berkembang.
Sementara di Surakarta, Pakubuwana IV maupun Pangeran Adipati Arya Mangkunegara II (1796-1835), berusaha mengisolasikan Yogyakarta dan meminta kepada pihak Belanda untuk berbalik melawan Sultan Hamengkubuwana II. Pakubuwana IV juga berusaha mengambil hati pihak Belanda, tetapi pada saat yang sama bertindak seolah-olah bersahabat dan ramah terhadap Hamengkubuwana II. Tujuannya adalah merekayasa kehancuran Yogyakarta, karena hubungan Hamengkubuwana II dengan pihak Belanda semakin memburuk dan perlawanan di daerah kekuasaannya semakin besar, maka jelaslah bahwa Pakubuwana IV akan menjadikan Hamengkubuwana II menjadi bulan-bulanan dari musuh-musuhnya.
6. Masa Pendudukan Pemerintah Kolonial Perancis di Jawa
Pada tahun 1808 mulai berlangsung suatu zaman baru dalam hubungan Jawa-Eropa. Negeri Belanda telah berada di bawah kekuasaan Perancis sejak tahun1975. sehubungan dengan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar, maka Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon sebagai penguasa di negeri Belanda pada tahun 1806. pada tahun 1808, Louis mengirim marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia untuk menjadi gubernur jenderal (1808-1811) dan untuk memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis melawan Inggris di Hindia.
Daendels adalah seorang pemuja prinsip-prinsip pemerintahan yang revolusioner. Dia membawa prisnsip tersebut ke Jawa sebagai suatu perpaduan antara semangat pembaharuan dan metode-metode kedidaktoran, yang sebenarnya hanya menuai sedikit hasil dan justru banyak perlawanan. Dia berusaha memberantas ketidakefisienan, penyelewengan, dan korupsi yang meliputi administrasi Eropa, tetapi banyak dari langkah-langkah pembaharuannya tak begitu berhasil. Dia memiliki perasaan tidak suka yang muncul dari naluri-naluri anti feodalnya, terhadap para penguasa Jawa (bupati) di daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Bagi Daendels, mereka bukan penguasa atau pemimpin atas masyarakat mereka melainkan pegawai administrasi Eropa. Dia pun mengurangi wewenang dan penghasilan mereka. Akan tetapi, Hamengkubuwana II tetap saja mengabaikannya dan menentang semua yang diwakili oleh Daendels.
Sementara itu, tanggapan-tanggapan Pakubuwana IV yang semakin cerdik meyakinkan Daendels bahwa dia bersedia bekerjasama , tetapi hamengkubuwana II sedang bersiap-siap melancarkan perang. Sebenarnya, Sultan hamenkubuwana II belum bermaksud melancarkan perang total pada tahap ini, tetapi kecurigaan Daendels telah memperbesar telah memperbesar ancaman bahaya terhadap posisi Yogyakarta. Pada tahun 1810, kepala pemerintahan Sultan untuk wilayah-wilayah luar (mancanegara), yaitu Raden Rangga melancarkan sebuah pemberontakan terhadap pemerintahan Eropa. Raden Rangga merupakan saudara ipar sultan dan mendapatkan dukungan secara diam-diam dari sultan dan kalangan bangsawan Yogyakarta. Pemberontakan ini berhasil ditumpas dengan mudah dan Raden Rangga terbunuh, tetapi putranya yang bernama Sentot masih hidup untuk memainkan peranan penting dalam Perang Jawa.
Pemberontakan Raden Rangga menyebabkab dikeluarkannya ultimatum oleh daendels yang ditujukan kepada Hamengkubuwana II. Dia harus menyetujui perubahan terhadap upacara istana yang berkaitan dengan kedudukan Minister Eropa”, mengangkat kembali Danureja II dengan kekuasaan penuh dan bertanggung jawab atas pemberontakan Rangga. Sultan menolak sehingga pada bulan Desember 1810, daendels bergerak menuju Yogyakarta dengan membawa 3200 serdadu dan memaksa Hamengkubuwana II turun tahta dan menyerahkannya kepada putranya yang kini menjadi ’wakil raja’ (Hamengkubuwana III).
Pada bulan Januari 1811, Daendels memaksakan perjanjian-perjanjian ke dalam wilayah pemerintahan Belanda, kepada Surakarta maupun Yogyakarta. Sesuai dengan anggapan Daendels bahwa pemerintah koloniallah yang berdaulat, maka uang sewa daerah pesisir yang selama ini telah dibayarkan oleh batavia sejak tahun 1746, kini dihapuskan. Dengan demikan, dengan sekali pukul Daendels telah menghapuskan insentif finansial yang paling penting bagi istana-istana Jawa untuk bersedia menerima pemerintahan orang-orang Eropa atas daerah pesisir dan meniadakan sumber utama penghasilan istana. Pada bulan Mei 1811, kedudukan Daendels sebagai gubernur jenderal digantikan oleh Jan Willem Janssens yang telah menderita penghinaan akibat menyerahkan tanjung Harapan kepada pihak Inggris pada tahun 1806. Dia mampu bertahan cukup lama di Jawa hanya untuk melakukan hal yang sama.
Pada tanggal 4 Agustus 1811, enam puluh kapal Inggris muncul di depan Batavia dan pada tanggal 26 Agustus kota tersebut berikut daerah-daerah sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Janssens mundur ke Semarang, di mana legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta dan Surakarta bergabung dengannya. Pihak Inggris berhasil mundur mereka, dan pada tanggal 18 September Janssens menyerah di dekat Salatiga. Seiring dengan penaklukan Jawa oleh Inggris, Sultan Hamengkubuwana II memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kembali tahta Yogyakarta, akan tetapi dia salah menilai tanda zaman, sehingga tindakannya itu segera disusul dengan terjadinya serangkaian peristiwa yang menimbulkan malapetaka bagi Jawa.
7. Masa Pendudukan Pemerintah Kolonial Inggris di Jawa
Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa (1811-1816). Jika Hamengkubuwana mengira bahwa pemerintahan Raffles akan berbeda dari pemerintahan Daendels, maka akan segera terbukti bahwa apa yang dilakukan Hamengkubuwana II adalah salah. Raffles adalah seorang pembaharu dan penentang ”despotisme” sebagaimana Daendels.
Pada mulanya Raffles membiarkan semua tindakan Hamengkubuwana II, tetapi segera jelas bahwa Sultan adalah orang yang keras dan tegas yang tidak diharapkan kerjasamanya oleh pihak Inggris. Pada bulan November 1811, John Crawfurd tiba di Yogyakarta sebagai residen yang baru (1811-1816). Dia adalah seorang yang pandangan-pandangannya tidak dapat diubah. Salah satu diantaranya adalah Hamengkubuwana II tidak dapat dipercaya. Dia melontarkan dan sekaligus menerima hinaan dan cercaan di istana sampai akhirnya dia menarik kesimpulan bahwa hanya langkah-langkah yang paling keraslah yang akan dapat mengubah situasi. Raffles memerintahkannya untuk bertindak hati-hati sampai datangnya pasukan yang cukup besar. Dengan keadaan dan situasi yang seperti ini, mulai kelihatan bahwa seakan-akan nyawa putra mahkota (Hamengkubuwana III), yang didukung Inggris terancam bahaya di istana ayahnya. Di waktu yang sama, Pakubuwana IV melibatkan diri ke dalam konflik tersebut. Secara diam-diam Pakubuwana IV mengadakan surat-menyurat dengan Hamengkubuwana II yang menyebabkan Sultan Hamengkubuwana II percaya bahwa Surakarta akan mendampinginya dalam perlawananbersenjata terhadap pemerintah Eropa. Tujuan Susuhunan yang sesungguhnya ialah mendorong supaya sultan menjadi berani melawan Inggris, sehingga akan menyebabkan hancurnya kesultanan di tangan orang-orang Eropa. Pihak Inggris segera mengetahui adanya surat-menyurat antara Surakarta-Yogyakarta. Mereka mulai mengadakan perundingan-perundingan rahasia dengan putra mahkota Yogyakarta (Hamengkubuwana III) dan Natakusuma dan bersiap-siap menghncurkan Yogyakarta.
Pada bulan Juni 1812, 1.200 prajurit berkebangsaan Eropa dan Sepoy India, didukung 800 Legiun Mangkunegara berhasil merebut istana Yogyakarta setelah tembakan-tembakan arteleri yang seru. Pakubuwana IV tidak berbuat apa-apa kecuali menempatkan pasukannya di seberang jalur-jalur komunikasi Inggris. Istana Yogyakarta dirampok, perpustakaan dan arsipnya dirampas, sejumlah besar uang diambil dan Hamengkubuwana II dimakzulkan dan dibuang ke Penang. Kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh putrannya, Hamengkubuwana III. Natakusuma, atas bantuannya kepada pihak Inggris, dihadiahi suatu daerah yang merdeka dan dapat diwariskan yang meliputi 4.000 rumah tangga di wilayah-wilayah Yogyakarta dan dianugerahi gelar Pakualam I (1813-1839). Dengan demikian, Pakualam di yogyakarta merupakan cerminan dari Mangkunegaran di Surakarta, dan lengkaplah sudah pembagian kerajaan Mataram ke dalam dua kerajaan senior dan dua yunior. Dibentuk pula korps Pakualam yang terdiriatas prajurit kaveleri, akan tetapi tidak seperti Legiun Mangkunegara, korps ini tidak pernah mempunyai arti yang penting dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1892.
Dampak penaklukan atas Yogyakarta tidak dapat dibuat berlebihan. Ini terjadi sekali dalam sejarah Jawa, ketika sebuah istana direbut dengan serangan oleh pasukan pemerintahan bangsa Eropa. Kalangan bangsawan Yogyakarta merasa sangat dihina. Raffles merebut banyak wilayah, baik daerah-daerah luar Yogyakarta maupun Surakarta, sehingga banyak pejabat tinggi kehilangan tanah. Pihak Inggris juga mengambil alih pengelolaan atas cukai lalu lintas dan pasar-pasar. Cukai-cukai tersebut kemudian disewakan kepada orang-orang cina, yang telah mengelolanya sejak abad sebelumnya, tetapi kini pengelolaan tersebut ditandai oleh semakin menigkatnya penyelewengan dan pemerasan terhadap orang-orang Jawa.
8. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda
Pada tahun 1816, Jawa dan pos-pos Indonesia lainnya dikembalikan kepada pihak Belanda sebagai bagian dari penyusunan kembali secara menyeluruh urusan-urusan Eropa setelah perang-perang Napoleon. Raffles sudah meninggalkan Jawa dan kembali ke Inggris, dia akhirnya akan terkenal sekali sebagai pendiri Singapura pada tahun 1819. Dari tahun 1812 sampai tahun 1825, perasaan tidak senang semakin meningkat di Jawa karena belum terselesaikannya beberapa persoalan. Orang-orang Eropa masih tetap melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan istana pada umumnya, dan khususnya dalam pergantian raja di Yogyakarta. Korupsi dan persengkongkolan semakin merajalela di kedua istana. Orang-orang Eropa dan cinamenyewa tanah yang bertambah luas di Jawa Tengah untuk dijadikan perkebunan-perkebunan tebu, kopi, nila, dan lada, terutama dari kalangan bangsawan yang membutuhkan uang.
Di perkebunan-perkebunan tersebut, penduduk pedesaan Jawa dan hukum adat dipandang rendah. Para petani semakin terpaksa untuk membayar pajaknya dalam bentuk kontan, yang mendorong mereka untuk meminjam uang dari para lintah darat, kebanyakannya adalah orang cina. Penguasa-penguasa cina dan penyewa pajak cina memainkan peran yang semakinmenonjol dalam masyarakat pedesaan Jawa. Ini semua meningkatkan ketegangan etnis antara cina dan Jawa. Penderitaan yang dialami masyarakat Jawa mengakibatkan terjadinya dislokasi sosial, dan gerombolan-gerombolan perampok semakin bertambah banyak dan berani. Pemakaian opium meluas di kalangan penduduk Jawa sebagai konsekuensi disloakasi semacam itu, yang meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial.
Di tengah-tengah keadaan yang menjadi dan semakin kacau itu, tampilah salah seorang tokoh yang sangat termasyur dalam sejarah Indonesia, yaitu Pangeran Dipanegara (1785-1855). Sebagai putra tertua Sultan Hamengkubuwana III, dia tumbuh menjadi dewasa di tengah-tengah persengkongkolan-persengkongkolan dan kekacauan yang timbul selama masa pemerintahan Hamengkubuwana II. Selama hampir dua puluh tahun, Dipanegara menatian waktunya yang baik. Selama masa itu, situasi di Jawa bertambah buruk dan pengikut Dipanegara bertambah banyak. Pada tahun 1820-an, pemberontakan-pemberontakan kecil mulai meletus.
Pada tahun 1821, panen padi tidak memuaskan dan penyakit kolera berjangkit di Jawa untuk pertama kalinya. Pada tahun 1822, Hamengkubuwana IV (1814-1822) wafat di tengah-tengah tersebarnya desas-desus bahwa dia diracun. Terjadi perdebatan-perebatan sengit dalam soal penunjukkan wali bagi putranya yang berumur tiga tahun, Hamengkubuwana V. Pada akhir tahun 1822, gunung Merapi meletus dengan dahsyat. Hal ini dianggap sebagai pertanda tentang akan terjadinya kekacauan. Bibit-bibit perang yang sudah tertanam pada diri Dipanegara sejak tahun 1808, kini segera tumbuh mencapai kematangannya. Pada tahun 1823, Gubernur Jenderal G.A.G.Ph. Van Der Capellen (1816-1826) mengambil keputusan untuk mengakhiri penyelewengan-penyelewengan di seputar penyewaan tanah swasta di Jawa Tengah. Dia memerintahkan agar sewa-menyewa semacam itu dihapuskan.
Para bangsawan yang telah menyewakan tanah mereka, kini tidak hanya kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga harus mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh penyewa-penyewa cina dan Eropa (yang umunya sudah harus dibelanjakan) dan membayar ganti rugi kepada mereka atas berbagai perbaikan yang telah mereka lakukan di tanah-tanah tersebut (yang kebanyakannya tidak berharga bagi para bangsawan, yang telah berkeinginanmengolah tanah-tanah mereka menjadi perkebunan). Inilah langkah terakhir yang telah mendorong banyak bangsawan melancarkan pemberontakan. Sebuah jalan raya baru akan dibangun di dekat Tegalreja pada bulan Mei 1825. suatu bentrokan antara para pengikut Dipanegara dengan para pengikut musuhnya, Patih Danureja IV (1813-1847), terjadi ketika patok-patok untuk jalan raya tersebut dipancangkan. Sesudah itu, berlangsung suatu periode ketegangan. Pada tanggal 20 Juli, pihak Belanda mengirim serdadu-serdadu dari yogyakarta untuk menangkap Dipanegara, sehingga menimbulkan perang terbuka. Tegalreja direbut dan dibakar, tetapi Dipanegara berhasil meloloskan diri dan mencanangkan panji pemberontakan, yaitu perang Jawa (1825-1830) pun dimulai.
Pemberontakan tersebut dengan cepat tersebar di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi pusatnya adalah kawasan Yogyakarta. Lima belas dari 29 pangeran, demikian pula 41 dari 88 bupati (pejabat senior istana), bergabung dengan Dipanegara. Dengan menjalarnya serangan-serangan pihak pemberontak terhadap orang-orang Cina dan Eropa, maka mulai terancamlah kekuasaan pemerintahan Belanda di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akan tetapi, pada akhir tahun 1825 sudah tampak jelas bahwa pihak pemberontak tidak akan dapat mengusir orang-orang Belanda dari Jawa dengan mudah.
Pada tahun 1827 pihak Belanda berhasil mengetahui bagaimana cara yang terbaik untuk memamfaatkan serdadu-serdadu mereka. Mereka menerapkan benteng stelsel (sistem benteng). Dengan sistem ini satuan-satuan kecil dapat beroperasi secara bebas dari jaringan pos-pos berbentang yang strategis yang selalu berkembang dan secara permanen mengawasi penduduk setempat. Gerombolan-gerombolan pemberontak dipaksa bertempur sebelum mereka sempat tumbuh dalam jumlah yang besar dan dicegah untuk tinggal lama di setiap daerah. Setelah tahun 1827 Dipanegara dan pasukan-pasukannya terus dikejar-kejar dan terjepit. Kolera, malaria, dan disentri menelan banyak korban di kedua belah pihak, tetapi pada tahun 1828 tampak jelas bahwa perang telah berbalik menguntungkan pihak Belanda dan sekutu-sekutunya.
Pembelotan dan jumlah tawanan dari pihak pemberontak semakin meningkat. Pada bulan April 1829 Kyai Maja ditangkap. Pada bulan September 1829 paman Dipanegara, yaitu pengeran Mangkubumi dan panglima utamanya Sentot kedua-duanya menyerah. Sentot kelak akan menjalankan tugas dipihak pemerintah melawan kaum Padri di Sumatera, sedangkan Mangkubumi diangkat sebagai salah satu dari pangeran-pangeran yang paling senior dari Yogyakarta. Akhirnya pada bulan Maret 1830 Dipanegara bersedia melakukan perundingan-perundingan di Magelang dan akhirnya ditangkap oleh Belanda kemudian diasingkan ke Manado dan Makasar. Di pihak pemerintah perang ini telah menelan 8.000 serdadu berkebangssaan Eropa dan 7.000 berkebangsaan Indonesia serta sedikitnya 200.000 orang Jawa telah tewas dalam perang Jawa.
KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Konflik yang terjadi di antara bangsawan Keraton Mataram disebabkan karena adanya keinginan para bangsawan Keraton Mataram untuk tetap mendapatkan pengangkuan tentang keberadaannya sebagai golongan yang berperan dalam melakukan dan melaksanakan kewenangannya sebagai penguasa budaya tradisional maupun pemerintahan di wilayah Jawa.
2. Peperangan yang terjadi Jawa dalam mengembalikan kemerdekaan dan kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa mengalami kegagalan. Kegagalan terjadi karena adanya penguasa lokal dan pangeran yang telah memihak kolonial Belanda. Keterpihakan mereka ke kolonial Belanda disebabkan hanya untuk mendapatkan pengakuan akan eksistensi penguasa lokal dan pangeran yang ingin berkuasa di Jawa. Dengan demikian kalangan Jawa yang konservatif telah berhasil menang dalam perdamaian yang diciptakan oleh pemerintahan kolonial, walaupun bangsawan yang lebih dinamis telah menderita kalah dalam perang.
3. Perang Jawa merupakan suatu gerakan konservatif dari kelompok elite bangsawan Jawa atas meningkatnya kekuatan kolonial di lingkungan Istana kerajaan-kerajaan Jawa. Luasnya gerakan protes sosial yang mendukung langkah perang Jawa nyata-nyata hanya untuk menunjukkan kebencian terhadap revolusi penjajahan yang telah merobek-robek masyarakat Jawa dan dalam hal ini perang Jawa seakan-akan membayangi gerakan anti penjajahan dari abad XX.
4. Peperangan yang terjadi Jawa dalam mengembalikan kemerdekaan dan kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa mengalami kegagalan. Kegagalan terjadi karena adanya penguasa lokal dan pangeran yang telah memihak kolonial Belanda. Keterpihakan mereka ke kolonial Belanda disebabkan hanya untuk mendapatkan pengakuan akan eksistensi penguasa lokal dan pangeran yang ingin berkuasa di Jawa. Dengan demikian kalangan Jawa yang konservatif telah berhasil menang dalam perdamaian yang diciptakan oleh pemerintahan kolonial, walaupun bangsawan yang lebih dinamis telah menderita kalah dalam perang.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufik, dkk. 1985. Ilmu Sejarah dan Historiografi. PT. Gramedia.
Jakarta.
De Graaft, HJ. 1990. Puncak Kekuasaan Mataram ; Politik Ekspansi Sultan
Agung, Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
Georges Balandier. 1996. Antropologi Politik. Penerjemah : Y. Budisantoso. PT.
Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Gertrude Himmelfard. 1987. The New History and The Old. Cambridge-
Massachusetts : The Belknap Press Of Havard University Press.
Gilbert J. Garrachan. 1982. A Guide To Historical Method. Loyola University.
Chicago.
Hadari Nawawi. 1991. Metode Pnelitian Bidang Sosial. Gajah Mada Press.
Yogyakarta.
H.C. Ricklefs. 2005. Sejarah Indonesia Modern. 1200–2005. Gajah Mada Press.
Jogyakarta.
Kuntowijoyo. 1994. Metodologi Sejarah. PT. Tiara. Yogyakarta.
Louis Gottschalk. 1986. Understanding History. Penerjemah Nugroho
Notosusanto. Cetakan ke-4. UI-Press. Jakarta.
Marwati Djoened. P. & Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia IV. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.
Nugroho Notosusanto. 1984. Masalah Penelitian Sejarah Kotemporer. Inti Indayu
Press. Jakarta.
Purwadi. 2007. Sejarah Raja-Raja Jawa. Yogyakarta: Media Ilmu.
Sartono Kartodirdjo. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah.
PT. Gramedia. Jakarta.
Sutrasno. 1975. Sejarah dan Ilmu Pengetahuan. Pradnya Paramita. Jakarta.
S. Margana. 2004. Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874. Pustaka Pelajar
dan The Toyota Foundation. Yogyakarta.
http//www//wordpress.com/../3_evolusi-ekonomi-kota-solo20-nopember 2007.pdf – Mirip diakses 15 Mei 2010.
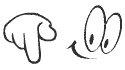



0 komentar:
Posting Komentar