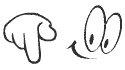Fasisme: Catatan Kecil dari Ebenstein
Paham fasisme mencuat ketika dimulainya masa Perang Dunia II. Setidaknya perang yang muncul saat itu, terjadi sebagai akibat perkembangan ideology fasis di Italia, Jerman dan Jepang, yang ingin meluaskan pengaruh ekstra-nasionalisnya. Sehabis berlangsungnya Perang Dunia II, ideologi fasisme seakan-akan berakhir, tetapi hal yang terjadi tidak nyata demikian. Sebagai sebuah produk pemikiran, benih-benih fasisme akan terus ada selama terdapat kondisi obyektif yang membentuknya.
Ebenstein mencatat bahwa “jika komunisme adalah pemberontakan pertama terhadap liberalisme, maka fasisme adalah pemberontakan kedua”. Fasisme muncul dengan pengorganisasian pemerintahan dan masyarakat secara totaliter, kediktatoran partai tunggal yang bersifat: ultra-nasionalis, rasis, militeris dan imperialis. Fasisme juga muncul pada masyarakat pasca-demokrasi dan pasca-industri. Jadi, fasisme hanya muncul di negara yang memiliki pengalaman demokrasi. Hal- hal yang penting dalam penbentukan suatu karakter negara fasis adalah militer, birokrasi, prestise individu sang diktator dan terpenting, dukungan massa. Semakin keras pola kepemimpinan suatu negara fasis, semakin besar pula dukungan yang didapatnya.
Latar Belakang Fasisme
Kondisi penting lainnya dalam pertumbuhan negara fasis adalah perkembangan industrialisasi. Munculnya negara industri, memunculkan ketegangan sosial dan ekonomi. Jika liberalisme adalah penyelesaian ketegangan dengan jalan damai yang mengakomodasi kepentingan yang ada, maka fasisme mengingkari perbedaan kepentingan secara paksaan. Fasisme mendapat dukungan pembiayaan dari industriawan dan tuan tanah, karena kedua kelompok ini mengharapkan lenyapnya gerakan serikat buruh bebas, yang dianggapnya menghambat kemajuan proses produksi dalam industri. Sumber dukungan lain bagi rezim fasis adalah kelas menengah, terutama pegawai negeri. Mereka melihat fasisme adalah sebuah sarana untuk mempertahankan prestise yang ada sekaligus perlindungan politik. Fasisme juga memerlukan dukungan dari kaum militer, sebagaimana fasisme Jerman, Italia dan Jepang, sebagai jalan menuju militerisasi rakyat.
Meskipun fasisme bukan merupakan akibat langsung dari depresi ekonomi, sebagaimana teori marxis, tetapi jelas kaum fasis memanfaatkan hal itu. Banyaknya angka pengangguran akibat depresi, melahirkan kelompok yang secara psikologis menganggap dirinya tidak berguna dan diabaikan. Saat hal ini terjadi, maka fasisme bekerja dengan memulihkan harga diri mereka, dengan menunjukkan bahwa mereka adalah ras unggul sehingga mereka merasa dimiliki. Dengan modal inilah, maka fasisme juga memperoleh dukungan dari rakyat lapisan bawah.
Dengan demikian, fasisme bekerja pada setiap lapisan masyarakat. Fasisme memanfaatkan secara psikologis kesamaan-kesamaan pokok yang ada seperti: frustasi, kemarahan dan perasaan tak aman. Tak aneh, jika dalam sejarahnya rezim fasis senantiasa mendapatkan dukungan masyarakat. Terutama hal ini jelas terjadi di Jerman.
Akar-akar Psikologis Totaliterisme
Petunjuk ke arah pemahaman fasisme terletak pada kekuatan dan tradisi masyarakatnya. Di Jerman, Jepang dan Italia, tradisi otoritarianisme sudah menjadi hal yang terjadi berabad-abad. Sehingga munculnya rezim fasis merupakan hal yang biasa. Dengan cara hidup otoriter maka jalan menuju otorianisme hanya menunggu waktunya saja. Munculnya kediktatoran secara politik, ditandai dengan munculnya pemimpin yang menggebu-gebu meraih kekuasaan dan memiliki hasrat yang kuat untuk mendominasi.
Namun demikian antara sang diktator dan fasisme juga dipengaruhi iklim suatu masyarakat. Ada kalanya iklim suatu negara lebih mudah menerima kediktatoran dibandingkan dengan negara lainnya. Jerman, Italia dan jepang mungkin adalah tipekal negara demikian. Adanya gerakan massa yang otoriter dalam fasisme justru ditentukan oleh hasrat banyak orang untuk memasrahkan diri dengan setia. Hal ini tentunya tidak dapat diamati dari sudut pandang rasionalitas. Fasisme ibarat memanfaatkan kondisi psikologis kepatuhan sang anak kepada orang-tuanya. Dengan kepatuhan, maka sang anak akan terlindungi karena memiliki tempat bergantung.
Fasisme juga memiliki ciri untuk menyesuaikan diri dengan praktek kuno yang sudah ada. Mementingkan status dan kekuatan pengaruh, kesetiaan kelompok, kedisiplinan dan kepatuhan yang membabi-buta. Hal ini menyatu dalam membentuk karakter fasis. Sehingga sebagai suatu kesatuan, mereka hanya patuh terhadap perintah tanpa harus mempersoalkan apa dan bagaimananya.
Sebagai cara mempertahankan kesatuan, fasisme juga menciptakan musuh-musuh yang nyata maupun imajiner. Jerman memusuhi yahudi, karena yahudi dianggap ras rendah yang senantiasa mengotori kemurnian ras arya. Memusuhi kaum komunis maupun liberalis-kapital, karena mereka bukan bangsa arya atau indo-jerman. Jika merasa kekuatannya telah cukup untuk tidak sekedar berteori, maka kaum Fasis mulai menunjukkan sifat imperialisnya. Mereka akan menjanjikan kemenangan dalam permusuhan dengan bangsa lain. Kaum fasis senantiasa ingin menunjukkan bahwa mereka lebih unggul dari bangsa atau negara manapun. Nahasnya, apabila fasisme kalah, maka sang pemimpin fasis akan menjadi korban kehancuran rezimnya sendiri. Sejarah mencatat nasib tragis yang dialami Mussolini yang ditembak dan digantung oleh rakyatnya sendiri, setelah sebelumnya Italia mengumumkan kekalahannya dalam perang. Nasib Hitler mungkin sedikit lebih baik, karena ia “mati terhormat” tanpa harus tunduk kepada musuhnya.
Teori dan Praktek Fasisme
Doktrin dan Kebijaksanaan
Tidak seperti komunisme, fasisme tidak memiliki landasan prinsipil yang baku atau mengikat perihal ajarannya. Apalagi dewasa ini dapat dipastikan, bahwa fasisme tidak memiliki organisasi yang menyatukan berbagai prinsip fasis yang bersifat universal.
Namun demikian, bukan berarti fasisme tidak memiliki ajaran. Setidaknya para pelopor fasisme meninggalkan jejak ajaran mereka perihal fasisme. Hitler menulis Mein Kampft, sedangkan Mussolini menulis Doktrine of Fascism. Ajaran fasis model Italia-lah yang kemudian menjadi pegangan kaum fasis didunia, karena wawasannya yang bersifat moderat. Menurut Ebenstein, unsur-unsur pokok fasisme terdiri dari tujuh unsur:
Pertama, ketidak percayaan pada kemampuan nalar. Bagi fasisme, keyakinan yang bersifat fanatik dan dogmatic adalah sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak boleh lagi didiskusikan. Terutama pemusnahan nalar digunakan dalam rangka “tabu” terhadap masalah ras, kerajaan atau pemimpin.
Kedua, pengingkaran derajat kemanusiaan. Bagi fasisme manusia tidaklah sama, justru pertidaksamaanlah yang mendorong munculnya idealisme mereka. Bagi fasisme, pria melampaui wanita, militer melampaui sipil, anggota partai melampaui bukan anggota partai, bangsa yang satu melampaui bangsa yang lain dan yang kuat harus melampaui yang lemah. Jadi fasisme menolak konsep persamaan tradisi yahudi-kristen (dan juga Islam) yang berdasarkan aspek kemanusiaan, dan menggantikan dengan ideology yang mengedepankan kekuatan.
Ketiga, kode prilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan. Dalam pandangan fasisme, negara adalah satu sehingga tidak dikenal istilah “oposan”. Jika ada yang bertentangan dengan kehendak negara, maka mereka adalah musuh yang harus dimusnahkan. Dalam pendidikan mental, mereka mengenal adanya indoktrinasi pada kamp-kamp konsentrasi. Setiap orang akan dipaksa dengan jalan apapun untuk mengakui kebenaran doktrin pemerintah. Hitler konon pernah mengatakan, bahwa “kebenaran terletak pada perkataan yang berulang-ulang”. Jadi, bukan terletak pada nilai obyektif kebenarannya.
Keempat, pemerintahan oleh kelompok elit. Dalam prinsip fasis, pemerintahan harus dipimpin oleh segelintir elit yang lebih tahu keinginan seluruh anggota masyarakat. Jika ada pertentangan pendapat, maka yang berlaku adalah keinginan si-elit.
Kelima, totaliterisme. Untuk mencapai tujuannya, fasisme bersifat total dalam meminggirkan sesuatu yang dianggap “kaum pinggiran”. Hal inilah yang dialami kaum wanita, dimana mereka hanya ditempatkan pada wilayah 3 K yaitu: kinder (anak-anak), kuche (dapur) dan kirche (gereja). Bagi anggota masyarakat, kaum fasis menerapkan pola pengawasan yang sangat ketat. Sedangkan bagi kaum penentang, maka totaliterisme dimunculkan dengan aksi kekerasan seperti pembunuhan dan penganiayaan.
Keenam, Rasialisme dan imperialisme. Menurut doktrin fasis, dalam suatu negara kaum elit lebih unggul dari dukungan massa dan karenanya dapat memaksakan kekerasan kepada rakyatnya. Dalam pergaulan antar negara maka mereka melihat bahwa bangsa elit, yaitu mereka lebih berhak memerintah atas bangsa lainnya. Fasisme juga merambah jalur keabsahan secara rasialis, bahwa ras mereka lebih unggul dari pada lainnya, sehingga yang lain harus tunduk atau dikuasai. Dengan demikian hal ini memunculkan semangat imperialisme.
Terakhir atau ketujuh, fasisime memiliki unsur menentang hukum dan ketertiban internasional. Konsensus internasional adalah menciptakan pola hubungan antar negara yang sejajar dan cinta damai. Sedangkan fasis dengan jelas menolak adanya persamaan tersebut. Dengan demikian fasisme mengangkat perang sebagai derajat tertinggi bagi peradaban manusia. Sehingga dengan kata lain bertindak menentang hukum dan ketertiban internasional.
Ekonomi Fasis
Ekonomi fasis menurut Ebenstein memiliki ciri negara korporasi. Dalam pemahaman ini, negara berkuasa untuk menata dan mengawasi system perekonomian. Negara fasis mengatur asosiasi modal dan tenaga kerja, dimana tenaga kerja diawasi dan asosiasi mendapatkan monopolinya. Dengan demikian negar berfunsi sebagai kelompok penengah.
Ada dua asumsi yang mendasari filsafat negara korporasi. Pertama,masyarakat biasa tidak boleh memikirkan hal-hal yang bersifat politik. Mereka hanya berhak menjalankan tugasnya sendiri-sendiri. Kedua, para elitlah yang dianggap memiliki kemampuan untuk memahami masalah seluruh anggota masyarakat. Karena itu hanya mereka yang berhak memerintah.
Demokrasi dengan tegas menolak hal ini. Demokrasi melihat bahwa aspek ekonomi dan politik adalah sesuatu yang tak terpisahkan. Selain itu sangat tidak mungkin para penguasa menggantikan “perasaan’ masyarakat yang dikuasai, terlebih lagi adanya prinsip kelas unggul di dalam masyarakat.
Bagi kaum fasis sendiri, Italia misalnya, negara korporasi bukanlah suatu respons atas kapitalisme maupun sosialisme liberal. Melainkan adalah suatu solusi kreatif dalam memikirkan kemakmuran ekonomi. Namun demikian, bagaimanapun fasisme yang totaliter tidak pernah mengizinkan persaingan bebas. Negara harus menunjukkan kuasanya diatas kepentingan atau unsur apapun.
Pada akhirnya, negara korporasi fasis terbukti kebangkrutannya. Saat Italia mulai dikalahkan oleh tentara sekutu pada Perang Dunia II, maka kepercayaan terhadap Il Duce juga memudar. Akhirnya, Mussolini harus merasakan hukuman mati dari rakyatnya sendiri.
Kasus “Fasisme” di Spanyol
Dalam melengkapi bahasannya, Ebenstein juga menceritakan mengenai keberadaan gerakan fasisme di Spanyol, di bawah pimpinan jendral Franco. Ebenstein mencatat bahwa ideology fasisme di Spanyol bertindak lebih moderat, karena pada awalnya ia hanya merupakan bentuk perkembangan kepentingan nasionalisme. Jendral Franco sendiri juga pada awalnya bukanlah seorang fasis, melainkan hanya militer biasa. Ia justru memanfaatkan kelompok Phalangis dalam menjalankan kekuasaannya. Berbeda dengan Fasisme Jerman dan Itali, dimana partailah yang memanfaatkan militer.
Bertahannya gerakan “fasis” franco lebih disebabkan karakter Spanyol yang agak berbeda dengan fasisme di Jerman maupun Italia. Di Spanyol, franco menjadi penguasa karena kemenangannya dalam perang saudara melawan kelompok republik. Ia juga mendapatkan dukungan kaum gerejawan, yang dipinggirkan dalam pemerintahan republik. Lebih penting, franco berkuasa atas negara yang baru mengembangkan industri dan baru bangkit sehabis perang, sehingga ketika Perang Dunia II terjadi, ia memilih untuk tidak melibatkan diri dalam persekutuan fasisme Italia-Jerman dan Jepang. Ketidak ikutsertaannyalah yang membuat rezim Franco mampu bertahan. Bahkan hingga kematiannya, ia masih di elukan oleh rakyatnya.
Namun demikian, pada akhirnya fasisme di Spanyol justru tumbang secara konstitusional dengan tahap kompromi yang lebih lunak. Dalam hal ini kelompok monarki Raja Juan Carlos memainkan hal yang penting, dan ternyata rakyat Spanyol juga tidak terlampau bereaksi karena perubahan yang ada. Lambat laun, Spanyol memasuki system liberalisme dan menjadi bagian masyarakat eropa.
Tanggapan terhadap bacaan
Tulisan ebenstein mengenai fasisme, mencoba mendudukkan ideology fasisme dalam tataran substansial. Ia melihat gejala fasisme sebagai suatu kondisi pada sebuah masyarakat, dan mungkin saja dapat terulang kembali. Tulisan ebenstein juga dikayakan dengan contoh kontemporer, yaitu kasus Spanyol.
Namun demikian, terdapat juga hal yang dirasakan kurang mengenai hal bagaimana fasisme mampu mempertahankan dukungan massa. Ebenstein hanya melihat adanya kekerasan sebagai suatu faktor pendukung, seakan melupakan faktor yang lainnya. Padahal, terdapat mekanisme penting yang dilupakan Ebenstein yaitu bagaimana kaum fasis menciptakan slogan atau ritus-ritus historis demi membangun karakter nasionalisme mereka. Bagaimanapun juga, jika kita mengamati munculnya negara fasis terdapat kecenderungan bahwa fasisme muncul pada negara yang memiliki identitas historis yang kuat.
Tentu bukan suatu kebetulan, selain menggunakan kekerasan, fasisme juga memanfaatkan parade atau aksi massa untuk memperkuat nasionalisme pendukungnya. Ketika Hitler atau Mussolini menciptakan gaya sapaan atau slogan dalam ritusnya, hal ini harus dilihat sebagai cara untuk menciptakan pola hubungan kharismatik (meminjam istilah Max Weber) antara penguasa dengan rakyatnya. Sehingga dalam konteks inilah hubungan patronase yang dikatakan ebenstein, dapat dilihat secara aktif. Secara psikologis, melihat manusia berduyun-duyun berkumpul memberi dukungan, maka akan menimbulkan nuansa sakralitas dan mitologis mengenai kemampuan komunal yang tak terkalahkan. Hitler lebih kuat fasismenya bukan hanya karena ia lebih kejam, melainkan juga karena ia mampu memanipulasi dengan cerdas symbol-symbol yang ada dalam masyarakat.
Faktor sejarah, juga merupakan kekuatan tersendiri. Hitler selalu mendengungkan “Third Reich”, Mussolini senantiasa mengatakan “Italia la Prima”, sedangkan Jepang senantiasa menunjukkan propaganda sebagai “Pemimpin Asia”. Ketika Hitler dan Mussolini menjabat sebagai kepala pemerintahan, maka keduanya juga membangun bangunan-bangunan megah sebagai symbol kejayaan suatu kekaisaran masa lampau. Bahkan Mussolini memperbaharui beberapa monumen Romawinya. Dengan kenangan masa lalulah, fasisme bergerak untuk menciptakan kejayaan di masa sekarang. Karena bagi mereka, hanya negara yang pernah unggul berhak atas sejarah dimasa sekarang. Dan inilah yang juga diandalkan oleh Hitler maupun Mussolini, dimana mereka mampu meyakinkan rakyatnya atas dasar keyakinan sejarah yang demikian.
Dalam konteks hubungan masa sekarang, ternyata ebenstein belum sampai pada kesimpulan penutup apakah masa depan fasisme masih ada. Pada titik inilah, terkadang muncul kealpaan kita dalam melihat keberadaan fasisme. Padahal fasisme yang rasis, sebagai suatu gagasan dan tindakan juga berada di mana-mana. Apakah benar yang ditunjukkan Paul Wilkinson (dan juga Harun Yahya), bahwa kekuatan kaum fasis sedang merasuki anak-anak generasi muda lewat gelombang musik punk dan skin head, dimana symbol nazisme senantiasa menjadi ikonnya. Atau apakah benar kelompok fasis sedang berupaya membangkitkan jati-dirinya kembali dengan hooliganisme di kancah sepak bola? Saya kira hal ini masih merupakan asumsi-asumsi yang harus dibuktikan oleh sejarah perihal kebenarannya.
Referensi
Ebenstein, William dan Edwin Fogelman. Isme-Isme Dewasa Ini, penerjemah: Alex Jemadu, Jakarta: Erlangga, 1990.
Hobsbawm, Eric. Age of Extremes, London: Abacus, 1994.
Wilkinson, Paul. New Fascist, Yogyakarta: Resist Book, 1995.
Sumber : http://newhistorian.wordpress.com/2008/01/04/fasisme/